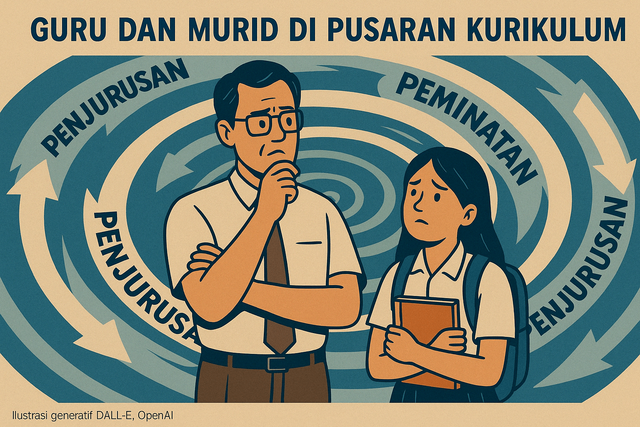Minggu lalu,
Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengumumkan dengan yakin bahwa penjurusan IPA, IPS,
dan Bahasa akan kembali diterapkan di SMA. "Jurusan akan kami hidupkan
lagi," tegasnya dalam diskusi dengan media. Keputusan ini datang hanya
beberapa tahun setelah Nadiem Makarim dengan sama yakinnya menghapus sistem
penjurusan tersebut dan menggantikannya dengan sistem peminatan dalam Kurikulum
Merdeka.
Dua Sisi Mata Uang yang Sama-sama Kusam
Mari jujur sejenak.
Baik sistem penjurusan maupun sistem peminatan Kurikulum Merdeka sama-sama
memiliki cacat bawaan. Ibarat memilih antara dua mobil bekas yang sama-sama
pernah tabrakan, kita dipaksa memilih mana yang "lebih baik" tanpa
opsi untuk mencari kendaraan yang benar-benar layak.
Sistem penjurusan lama
memang menimbulkan stigma dan segregasi. "IPA untuk anak pintar, IPS untuk
yang biasa-biasa, Bahasa untuk yang kurang mampu akademis." Begitulah
konstruksi sosial yang terlanjur mengakar. Tak heran jika Nadiem Makarim merasa
perlu mendobrak paradigma ini.
Namun Kurikulum Merdeka
dengan sistem peminatannya ternyata juga melahirkan masalah baru. Budy Sugandi
dari Yayasan Cendekia mengidentifikasi berbagai kekurangan, mulai dari
"siswa kebingungan memilih mata pelajaran sesuai bakat minat" hingga
"minimnya asesmen bakat minat potensi dan karier yang komprehensif."
Alih-alih memberikan
kebebasan yang memberdayakan, sistem peminatan justru menciptakan kebingungan
dan ketidakpastian. Siswa diberi kebebasan memilih tanpa bekal pemahaman yang
cukup tentang konsekuensi pilihannya. Seperti anak kecil yang dilepas di toko permen
dengan uang terbatas, tanpa pemahaman tentang nilai gizi dari masing-masing
permen.
"Terlalu dini di
kelas XI awal, siswa harus menetapkan profesinya apa kelak," ungkap
praktisi pendidikan Heriyanto dengan tepat. Bagaimana mungkin kita mengharapkan
kepastian arah hidup dari remaja yang identitasnya masih dalam proses
pembentukan?
Maju-Mundur tanpa Peta Jalan
Yang lebih menyedihkan
dari kontroversi ini bukanlah substansi kebijakan itu sendiri, melainkan pola
pengambilan keputusan yang reaktif dan terkesan egois.
Ada rasa getir ketika
menyadari bahwa Indonesia sebenarnya sudah memiliki "Peta Jalan Pendidikan
Indonesia 2025-2045" yang dirancang Bappenas. Dokumen yang seharusnya
menjadi kompas kebijakan pendidikan selama dua dekade ke depan. Tapi apa yang
terjadi? Dokumen itu seolah hanya pajangan di lemari kantor, dilupakan setiap
kali ada pergantian menteri.
"Jadi kita bisa
mengukur misalnya lima tahun Nadiem sudah sampai mana, maka Pak Abdul Mu'ti
melanjutkan, kan begitu," kata Koordinator Nasional Jaringan Pemantau
Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji dengan nada frustrasi. "Tapi ini kan
enggak, kesannya maju mundur."
Saya membayangkan
pendidikan kita sebagai sebuah bangunan yang tidak pernah selesai. Begitu
fondasinya terpasang, datang arsitek baru yang merasa perlu membongkar semua
dan memulai dari awal lagi. Begitu dinding mulai berdiri, datang lagi pemimpin
proyek baru dengan desain berbeda. Hasilnya? Sebuah bangunan aneh dengan
fondasi yang ditambal-sulam, dinding yang tidak simetris, dan atap yang bocor
di sana-sini.
Kurikulum Merdeka: Kebebasan yang Tidak Siap
Infrastruktur
Kritik terhadap
Kurikulum Merdeka bukan tanpa dasar. Dengan slogan "merdeka belajar,"
kurikulum ini menganut filosofi progressivisme dan konstruktivisme yang memang
ideal dalam teori pendidikan modern. Siswa sebagai pusat pembelajaran, guru
sebagai fasilitator, dan kebebasan untuk mengembangkan minat.
Tapi seperti demokrasi
yang datang ke negara tanpa tradisi demokratis, kebebasan tanpa infrastruktur
pendukung justru berpotensi melahirkan kekacauan.
Sekolah-sekolah elite
di kota besar mungkin mampu menyediakan guru berkualitas untuk berbagai
kombinasi mata pelajaran. Tapi bagaimana dengan sekolah di daerah terpencil
yang bahkan untuk mata pelajaran wajib saja masih kekurangan guru?
"Karena
keterbatasan jumlah guru dan jadwal, dan ketersediaan sarpras penunjang
mapel," jelas Budy Sugandi tentang kesulitan sekolah menyediakan sumber
daya untuk semua kombinasi mata pelajaran.
Saya teringat pepatah
lama: "Jangan berikan orang lapar sebuah resep masakan, berikan mereka
makanan." Kurikulum Merdeka seolah memberikan resep pendidikan ideal,
tanpa mempertimbangkan bahwa banyak sekolah kita masih berjuang dengan
kebutuhan dasar.
Penjurusan Kembali: Solusi atau Kemunduran?
Lantas, apakah
keputusan kembali ke sistem penjurusan merupakan langkah yang tepat? Tergantung
dari mana kita melihatnya.
Di satu sisi,
penjurusan memberikan struktur dan kejelasan arah bagi siswa. "Dengan
adanya penjurusan IPA, IPS dan Bahasa itu bagus agar siswa bisa mempelajari
ilmu sesuai dengan minatnya dan menjadi ahli," kata Ketua Umum PB PGRI
Unifah Rosyidi.
Penjurusan juga
memberikan kedalaman pemahaman yang lebih baik dalam satu rumpun ilmu. Siswa
tidak sekadar mencicipi banyak mata pelajaran secara dangkal, tapi mendalami
beberapa mata pelajaran yang saling terkait.
Namun di sisi lain,
kembali ke penjurusan bisa dianggap sebagai kemunduran. Kita kembali ke sistem
yang membatasi eksplorasi minat dan bakat siswa. Kita kembali ke kotak-kotak
yang kaku dan berpotensi melahirkan stigma sosial.
Yang lebih
memprihatinkan, kita kembali mengulangi siklus gonta-ganti kebijakan tanpa
evaluasi menyeluruh. "Biasanya pergantian kurikulum itu setiap sepuluh
tahun, ini belum sampai tiga tahun sudah ganti lagi," keluh Ketua Umum
Federasi Serikat Guru Indonesia, Fahmi Hatib.
Korban Sesungguhnya: Siswa dan Guru
Di tengah pertarungan
ego dan ideologi para elit pendidikan, siswa dan guru menjadi korban sebenarnya
dari ketidakpastian kebijakan ini.
Coba bayangkan perasaan
siswa kelas X yang baru masuk SMA tahun ini. Mereka memilih mata pelajaran
berdasarkan sistem peminatan, menyusun rencana akademik jangka panjang, lalu
tiba-tiba harus beralih ke sistem penjurusan saat naik ke kelas XI. Bagaimana
dengan mata pelajaran yang sudah mereka pilih namun tidak masuk dalam jurusan
yang harus mereka ambil?
Atau bagaimana dengan
guru-guru yang sudah bersusah payah mengikuti pelatihan Kurikulum Merdeka,
mengubah cara mengajar, menyesuaikan metode penilaian, dan kini harus kembali
ke sistem lama? Berapa banyak energi, waktu, dan sumber daya yang terbuang
percuma?
"Kasihan anak-anak
jadi kelinci percobaan, karena korbannya peserta didik, tapi yang lebih serius
lagi korbannya ya masa depan kualitas pendidikan di Indonesia yang terus
memburuk," kata Ubaid Matraji dengan tepat.
Jalan Tengah yang Terabaikan
Yang menyedihkan, debat
kebijakan pendidikan kita seringkali terjebak dalam dikotomi palsu: penjurusan
versus peminatan, tradisional versus progresif, disiplin versus kebebasan.
Padahal, jalan tengah yang mengambil kelebihan dari kedua sistem mungkin justru
yang kita butuhkan.
Bagaimana jika kita
mempertahankan kerangka penjurusan untuk memberikan struktur dan kedalaman,
tapi dengan fleksibilitas tertentu yang memungkinkan eksplorasi lintas jurusan?
Bagaimana jika kita memberi siswa kebebasan memilih dalam batasan yang
realistis sesuai kapasitas sekolah?
Sayangnya,
pikiran-pikiran semacam ini terbenam dalam hiruk-pikuk kebijakan yang serba
hitam-putih. Para pemangku kebijakan seperti lebih tertarik membuat gebrakan
dramatis daripada perbaikan sistematis yang mungkin kurang seksi secara
politis.
Menuju Pendidikan yang Bermartabat
Jika kita benar-benar
ingin memajukan pendidikan Indonesia, kita perlu menghentikan siklus
gonta-ganti kebijakan yang memusingkan ini. Kita perlu membangun sistem pendidikan
yang benar-benar berpusat pada kebutuhan siswa dan realitas lapangan, bukan
pada ego pejabat atau tren kebijakan global.
Pertama, kita butuh
konsistensi. Mari beri waktu sebuah kurikulum untuk berakar dan berbuah sebelum
mencabutnya dan menanam yang baru. Setidaknya biarkan satu angkatan lulus
dengan kurikulum tersebut agar kita punya data konkret tentang keberhasilan
atau kegagalannya.
Kedua, kita butuh
kontekstualisasi. Kebijakan yang sama tidak bisa diterapkan secara seragam di
seluruh Indonesia dengan kondisi yang sangat beragam. Mungkin sistem peminatan
cocok untuk sekolah-sekolah dengan sumber daya melimpah, sementara penjurusan
lebih realistis untuk sekolah dengan keterbatasan.
Ketiga, kita butuh
kebijakan yang memberdayakan guru di lapangan, bukan menambah beban
administrasi mereka. Guru adalah ujung tombak perubahan. Tanpa dukungan pada
mereka, kurikulum seindah apapun hanya akan menjadi dokumen mati.
Lebih dari itu, kita
butuh kerendahan hati para pembuat kebijakan untuk mengakui bahwa perubahan
dalam pendidikan membutuhkan waktu. Bahwa hasil dari investasi pendidikan tidak
bisa dilihat dalam hitungan bulan atau tahun, tapi dalam dekade.
Siswa-siswa kita bukan
kelinci percobaan di laboratorium kebijakan. Mereka adalah masa depan bangsa
yang berhak mendapatkan pendidikan terbaik. Pendidikan yang membebaskan, bukan
membingungkan. Pendidikan yang menginspirasi, bukan mengekang. Pendidikan yang
konsisten, bukan terombang-ambing mengikuti ganti menteri.
Sudah saatnya kita
memikirkan pendidikan Indonesia dengan lebih bermartabat, jauh dari ego
sektoral dan arogansi kekuasaan. Karena pilihan kita hari ini akan menentukan
Indonesia seperti apa yang akan kita serahkan pada generasi mendatang.
Salam
Cerdas dan Humanis.